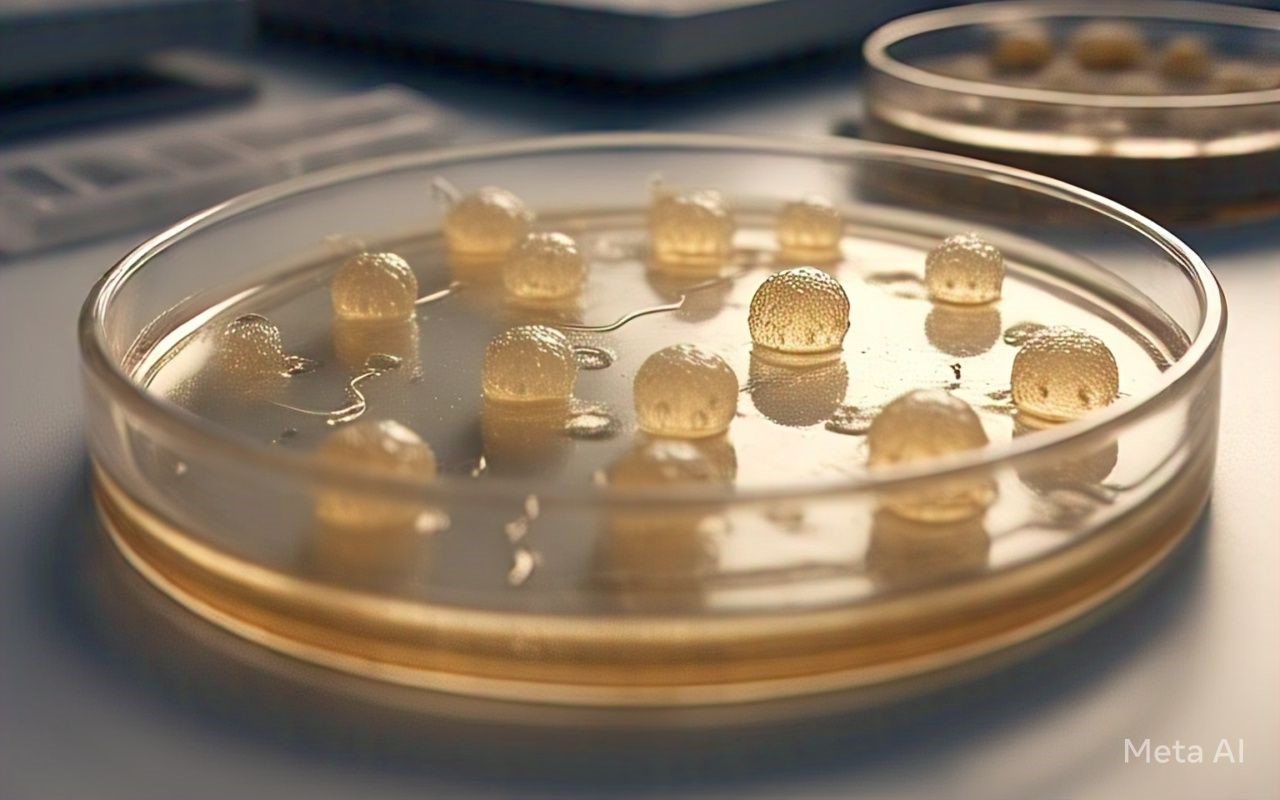Oleh: Untoro Hariadi
Indonesia, dengan keberagaman budaya dan sumber daya alamnya yang melimpah, memiliki kekayaan pengetahuan tradisional tentang pangan yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, di tengah arus modernisasi dan globalisasi yang semakin deras, pengetahuan lokal ini perlahan mulai terkikis, digantikan dengan sistem pangan modern yang seringkali tidak berkelanjutan dan tidak sesuai dengan kondisi lokal. Di sinilah konsep etnonutrisi menjadi penting sebagai pendekatan alternatif untuk mewujudkan desa cukup pangan yang mandiri dan berkelanjutan.
Pengetahuan Lokal
Etnonutrisi, secara sederhana, dapat dipahami sebagai pengetahuan tradisional suatu kelompok masyarakat atau etnis tertentu mengenai makanan, nutrisi, dan hubungannya dengan kesehatan. Pengetahuan ini mencakup jenis-jenis tanaman pangan yang dapat dikonsumsi, cara pengolahannya, serta nilai gizi dan khasiat yang terkandung di dalamnya. Lebih dari sekadar pengetahuan tentang makanan, etnonutrisi juga meliputi sistem kepercayaan, ritual, dan praktik budaya yang berkaitan dengan pangan, yang telah terbukti berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan kesehatan masyarakat.
Di berbagai daerah di Indonesia, nenek moyang kita telah mengembangkan sistem pangan yang sangat adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat. Mereka tahu persis kapan waktu yang tepat untuk menanam, jenis tanaman apa yang cocok ditanam bersamaan, bagaimana mengelola hama dan penyakit secara alami, serta bagaimana mengolah hasil panen agar tahan lama dan tetap bergizi. Di Jawa, misalnya, ada praktik tumpang sari yang mengombinasikan beberapa jenis tanaman dalam satu lahan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang dan nutrisi tanah. Di Papua, ada sistem perladangan berpindah yang, jika dikelola dengan bijak, justru dapat menjaga kesuburan tanah dan keanekaragaman hayati.
Namun, seiring dengan masuknya sistem pertanian modern yang mengandalkan bibit unggul, pupuk kimia, dan pestisida, banyak praktik tradisional ini yang mulai ditinggalkan. Padahal, jika ditelisik lebih dalam, praktik-praktik tersebut mengandung kearifan yang sangat relevan dengan tantangan pangan dan lingkungan yang kita hadapi saat ini.
Tanaman Lokal
Salah satu aspek penting dalam etnonutrisi adalah pemanfaatan tanaman pangan lokal. Indonesia memiliki ribuan jenis tanaman pangan lokal yang telah dibudidayakan dan dikonsumsi oleh masyarakat selama berabad-abad. Tanaman-tanaman ini umumnya sangat adaptif terhadap kondisi lingkungan setempat, tahan terhadap hama dan penyakit lokal, serta memiliki nilai gizi yang tinggi.
Ambil contoh jewawut atau millet, sebuah jenis serealia yang dulunya menjadi makanan pokok di beberapa daerah di Indonesia Timur. Jewawut memiliki kandungan protein, serat, dan mineral yang lebih tinggi dibandingkan beras, serta dapat tumbuh di lahan kering dengan input minimal. Atau garut, umbi-umbian yang kaya akan pati dan mudah dicerna, sehingga sering dijadikan makanan untuk orang sakit dan bayi. Belum lagi berbagai jenis kacang-kacangan dan umbi-umbian lokal yang kaya akan protein dan karbohidrat kompleks.
Sayangnya, banyak tanaman pangan lokal ini yang kini statusnya langka atau bahkan terancam punah karena tidak lagi dibudidayakan secara luas. Masyarakat lebih memilih menanam tanaman komersial yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi, meskipun seringkali tidak sesuai dengan kondisi lingkungan setempat dan membutuhkan input yang tinggi.
Padahal, jika dihidupkan kembali, budidaya tanaman pangan lokal ini bisa menjadi kunci untuk mewujudkan desa cukup pangan. Tanaman-tanaman ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjaga kelestarian lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada pasokan pangan dari luar.
Langkah Nyata
Etnonutrisi tidak hanya bicara tentang jenis tanaman, tetapi juga tentang bagaimana tanaman tersebut dibudidayakan, diolah, dan dikonsumsi. Dalam praktik pertanian tradisional, ada banyak metode yang terbukti efektif dalam menjaga kesuburan tanah dan mengendalikan hama secara alami.
Di beberapa daerah di Indonesia, masyarakat memiliki kalender tanam tradisional yang mengatur kapan waktu yang tepat untuk menanam, memanen, dan membiarkan lahan beristirahat. Kalender ini biasanya berbasis pada pengamatan terhadap tanda-tanda alam, seperti posisi bintang, perilaku hewan, atau fenomena alam lainnya. Metode ini memungkinkan petani untuk mengoptimalkan hasil panen tanpa merusak lingkungan.
Selain itu, praktik pertanian tradisional juga sering memanfaatkan berbagai jenis tanaman yang ditanam bersama-sama untuk saling mendukung. Misalnya, menanam kacang-kacangan yang dapat mengikat nitrogen dari udara untuk menyuburkan tanah, atau menanam tanaman aromatik yang dapat mengusir hama tertentu. Praktik-praktik ini, yang kini sering disebut sebagai agroekologi, sebenarnya telah lama dipraktikkan oleh masyarakat tradisional di berbagai belahan dunia.
Dalam hal pengolahan pangan, masyarakat tradisional juga memiliki berbagai metode untuk meningkatkan nilai gizi dan daya tahan makanan. Proses fermentasi, misalnya, tidak hanya dapat mengawetkan makanan, tetapi juga meningkatkan kandungan nutrisi dan memudahkan pencernaan. Tempe, tape, dan berbagai jenis makanan fermentasi lainnya adalah bukti nyata kearifan lokal dalam pengolahan pangan.
Tantangan
Meskipun memiliki banyak kelebihan, praktik etnonutrisi dan sistem pangan lokal menghadapi berbagai tantangan di era modern. Perubahan pola konsumsi masyarakat, terutama di kalangan generasi muda, adalah salah satu tantangan terbesar. Makanan cepat saji dan produk pangan olahan yang dipasarkan secara masif telah menggeser posisi makanan tradisional dalam menu sehari-hari masyarakat.
Selain itu, kebijakan pembangunan yang cenderung memfavoritkan pertanian skala besar dan monokultur juga menjadi hambatan bagi pelestarian sistem pangan lokal. Petani kecil, yang biasanya menjadi penjaga keanekaragaman tanaman pangan lokal, sering kali tidak mendapatkan dukungan yang memadai dari pemerintah.
Tantangan lain adalah hilangnya pengetahuan tradisional tentang pangan. Seiring dengan modernisasi dan urbanisasi, banyak pengetahuan tentang tanaman pangan lokal dan cara pengolahannya yang tidak terdokumentasi dengan baik dan hanya diturunkan secara lisan, akhirnya hilang ketika generasi tua meninggal dunia.
Solusi
Untuk mewujudkan desa cukup pangan berbasis etnonutrisi, diperlukan pendekatan terpadu yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari masyarakat lokal, pemerintah, akademisi, hingga sektor swasta.
Pertama, perlu ada upaya sistematis untuk mendokumentasikan dan melestarikan pengetahuan tradisional tentang pangan. Ini bisa dilakukan melalui penelitian partisipatif yang melibatkan masyarakat lokal, terutama para tetua yang masih memiliki pengetahuan mendalam tentang tanaman pangan lokal dan cara pengolahannya.
Kedua, diperlukan kebijakan yang mendukung pengembangan sistem pangan lokal dan berkelanjutan. Ini mencakup kebijakan pertanahan yang melindungi lahan pertanian tradisional, dukungan finansial dan teknis bagi petani kecil yang membudidayakan tanaman pangan lokal, serta regulasi yang memfasilitasi akses pasar bagi produk pangan lokal.
Ketiga, perlu ada edukasi dan kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang nilai gizi dan manfaat ekologis dari tanaman pangan lokal. Ini bisa dilakukan melalui berbagai saluran, mulai dari kurikulum sekolah, media massa, hingga festival kuliner tradisional.
Keempat, perlu ada inovasi dalam pengolahan dan pemasaran produk pangan lokal agar lebih sesuai dengan gaya hidup modern tanpa mengurangi nilai gizinya. Ini bisa mencakup pengembangan produk pangan olahan berbahan dasar tanaman lokal, pengemasan yang menarik, hingga pemanfaatan teknologi digital untuk pemasaran.
Kelima, perlu ada kerja sama lintas sektor untuk mendukung pengembangan desa cukup pangan berbasis etnonutrisi. Ini bisa berupa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan sektor swasta dalam berbagai program, mulai dari riset hingga pengembangan usaha.
Penutup
Etnonutrisi dan sistem pangan lokal bukan sekadar alternatif romantis di tengah dominasi sistem pangan global, melainkan solusi nyata untuk berbagai tantangan pangan dan lingkungan yang kita hadapi saat ini. Dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa dan kekayaan pengetahuan tradisional, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan desa-desa cukup pangan yang mandiri, berkelanjutan, dan berketahanan terhadap krisis.
Namun, untuk mewujudkan potensi ini, diperlukan komitmen dan kerja sama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mengambil peran lebih aktif dalam mendukung dan melindungi sistem pangan lokal melalui kebijakan yang tepat. Akademisi dan peneliti perlu lebih banyak mengeksplorasi dan mendokumentasikan kearifan lokal dalam bidang pangan. Komunitas dan masyarakat sipil perlu lebih vokal dalam mengadvokasi hak atas pangan dan pelestarian keanekaragaman hayati. Dan yang tidak kalah penting, kita semua sebagai konsumen perlu lebih menghargai dan mendukung produk pangan lokal.
Dengan pendekatan terpadu ini, bukan hal yang mustahil untuk mewujudkan desa-desa cukup pangan di seluruh Indonesia, di mana setiap keluarga memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan sesuai dengan preferensi budaya mereka, yang diproduksi secara berkelanjutan dan menghormati kearifan lokal. Inilah esensi dari etnonutrisi dan desa cukup pangan yang sesungguhnya.
Dr. Untoro Hariadi
Dosen Fakultas Pertanian Universitas Janabadra